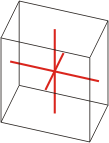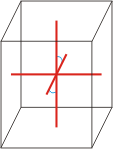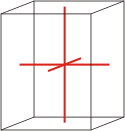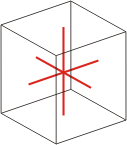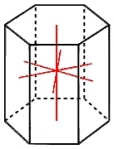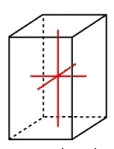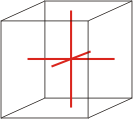TEKSTUR BATUAN BEKU
Secara umum batuan beku dapat dibedakan dari kenampakan bentuk, ukuran butir dan hubungan kristal mineral-mineralnya atau disebut sebagai tekstur batuan.
Beberapa tekstur batuan beku yang umum adalah:
1. Gelas (glassy)
2. Afanitik (aphanitic)
3. Fanerik (phaneritic)
4. Porfiritik (porphyritic)
5. Piroklastik (pyroclastic)
Gelas (Glassy), tidak berbutir atau tidak mempunyai kristal (amorf). Terjadi akibat magma membeku dengan cepat saat menyentuh atmosfer. Suhu dan tekanan di atmosfer jauh lebih rendah dibandingkan dengan dapur magma. Akibatnya tidak sempat membentuk kristal atau amorf, seperti obsidian. Kadang lava mendingin atau membeku dengan cepatnya sehingga atom-atomnya tidak sempat membentuk mineral, sehingga yang terbentuk ialah mineraloid. Batuan beku luar yang sebagian atau seluruhnya terdiri dari gelas dinamakan obsidian.
Afanitik - (fine grain texture) - (aphanitic dari bahasa Yunani phaneros yang berarti terlihat, dan a yang berarti tidak) dapat diartikan mineral-mineralnya tidak dapat diamati dengan mata telanjang. Memperlihatkan pembekuan yang cepat namun masih sempat membentuk kristal yang kecil. Melalui pengamatan di bawah mikroskop dapat dikenali sebagai feldspar dan kuarsa.
Faneritik (phaneritic), yang berarti dapat dilihat. Batuan dengan tekstur ini butiran mineralnya dapat dilihat tanpa mikroskop, memperlihatkan besar kristal yang hampir seragam dan saling mengunci (interlock). Bentuk kristal yang besar ini menyatakan bahwa pembekuannya berlangsung sangat lama di bawah permukaan bumi.
Porfiritik, merupakan tekstur yang khusus dimana terdapat campuran antara butiran kasar di dalam massa dengan butiran yang lenih halus. Butiran yang relative sempurna dinamakan fenokrist (phenocrysts), sedangkan butiran yang lebih kecil disebut massa dasar (groundmass). Tekstur porfiritik menunjukkan bahwa magma yang sebagian membeku bergerak ke atas dengan cepat lalu mendingin dengan cepat pula. Sehingga meghasilkan fenokris yang dikelilingi oleh massa dasar. Pegmatite, merupakan batuan beku dalam yang terdiri dari mineral-mineral yang berukuran tidak lazim, besar-besar, sampai 2 cm atau lebih.
Pyroklastik – (dalam bahasa Yunani pyro artinya api dan klastos adalah pecah). Dikatakan pyroklastik jika strukturnya mirip dengan porfiritik namun bila dilihat di bawah mikroskop bahwa butirannya lebih banyak pecah-pecah dari pada saling mengunci. Fragmennya juga bengkok, terpilin dan terdeformasi. Terjadi akibat erupsi ledakan material berukuran debu yang dihembuskan ke atas.
Beberapa tekstur batuan beku yang umum adalah:
1. Gelas (glassy)
2. Afanitik (aphanitic)
3. Fanerik (phaneritic)
4. Porfiritik (porphyritic)
5. Piroklastik (pyroclastic)
Gelas (Glassy), tidak berbutir atau tidak mempunyai kristal (amorf). Terjadi akibat magma membeku dengan cepat saat menyentuh atmosfer. Suhu dan tekanan di atmosfer jauh lebih rendah dibandingkan dengan dapur magma. Akibatnya tidak sempat membentuk kristal atau amorf, seperti obsidian. Kadang lava mendingin atau membeku dengan cepatnya sehingga atom-atomnya tidak sempat membentuk mineral, sehingga yang terbentuk ialah mineraloid. Batuan beku luar yang sebagian atau seluruhnya terdiri dari gelas dinamakan obsidian.
Afanitik - (fine grain texture) - (aphanitic dari bahasa Yunani phaneros yang berarti terlihat, dan a yang berarti tidak) dapat diartikan mineral-mineralnya tidak dapat diamati dengan mata telanjang. Memperlihatkan pembekuan yang cepat namun masih sempat membentuk kristal yang kecil. Melalui pengamatan di bawah mikroskop dapat dikenali sebagai feldspar dan kuarsa.
Faneritik (phaneritic), yang berarti dapat dilihat. Batuan dengan tekstur ini butiran mineralnya dapat dilihat tanpa mikroskop, memperlihatkan besar kristal yang hampir seragam dan saling mengunci (interlock). Bentuk kristal yang besar ini menyatakan bahwa pembekuannya berlangsung sangat lama di bawah permukaan bumi.
Porfiritik, merupakan tekstur yang khusus dimana terdapat campuran antara butiran kasar di dalam massa dengan butiran yang lenih halus. Butiran yang relative sempurna dinamakan fenokrist (phenocrysts), sedangkan butiran yang lebih kecil disebut massa dasar (groundmass). Tekstur porfiritik menunjukkan bahwa magma yang sebagian membeku bergerak ke atas dengan cepat lalu mendingin dengan cepat pula. Sehingga meghasilkan fenokris yang dikelilingi oleh massa dasar. Pegmatite, merupakan batuan beku dalam yang terdiri dari mineral-mineral yang berukuran tidak lazim, besar-besar, sampai 2 cm atau lebih.
Pyroklastik – (dalam bahasa Yunani pyro artinya api dan klastos adalah pecah). Dikatakan pyroklastik jika strukturnya mirip dengan porfiritik namun bila dilihat di bawah mikroskop bahwa butirannya lebih banyak pecah-pecah dari pada saling mengunci. Fragmennya juga bengkok, terpilin dan terdeformasi. Terjadi akibat erupsi ledakan material berukuran debu yang dihembuskan ke atas.

















 Berwarna putih, kelabu, atau kecoklatan, tak pernah ditemukan dalam bentuk kristal, merupakan produk alterasi magnesium silikat pada batuan ultramafik dan metasomatisme pada marmer dolomitik. Talk dipakai pada industri kertas, cat, karet, kosmetik, tekstil dan bubuk talk.
Berwarna putih, kelabu, atau kecoklatan, tak pernah ditemukan dalam bentuk kristal, merupakan produk alterasi magnesium silikat pada batuan ultramafik dan metasomatisme pada marmer dolomitik. Talk dipakai pada industri kertas, cat, karet, kosmetik, tekstil dan bubuk talk.

 Berbentuk kubik, warnanya sangat bervariasi mulai dari tidak berwarna hingga hitam, tidak larut dalam air, jika terkena sinar ultraviolet akan menimbulkan fluorescent, dapat ditemukan pada urat hidrotermal temperatur sedang hingga tinggi atau hasil dari sublimasi batuan vulkanik.
Berbentuk kubik, warnanya sangat bervariasi mulai dari tidak berwarna hingga hitam, tidak larut dalam air, jika terkena sinar ultraviolet akan menimbulkan fluorescent, dapat ditemukan pada urat hidrotermal temperatur sedang hingga tinggi atau hasil dari sublimasi batuan vulkanik. Tak berwarna hingga berwarna kuning, hijau dan coklat, beberapa jenis apatit bisa kehilangan warnanya jika dipanaskan, dan ada pula yang berpendar jika terkena sinar ultraviolet. Terdapat di semua jenis batuan, stabil hampir di setiap lingkungan, banyak ditambang untuk pupuk, serta merupakan penyusun utama pada gigi.
Tak berwarna hingga berwarna kuning, hijau dan coklat, beberapa jenis apatit bisa kehilangan warnanya jika dipanaskan, dan ada pula yang berpendar jika terkena sinar ultraviolet. Terdapat di semua jenis batuan, stabil hampir di setiap lingkungan, banyak ditambang untuk pupuk, serta merupakan penyusun utama pada gigi. Merupakan kelompok mineral yang terdiri dari plagioklas, potasium feldspar, dan feldspatoid dengan masing-masing anggotanya. Plagioklas merupakan feldspar yang mengandung Kalsium dan Natrium. Potasium feldspar merupakan feldspar yang mengandung Kalium. Sedangkan feldspatoid merupakan feldspar yang kekurangan silika. Terbentuk langsung dari kristalisasi magma, merupakan salah satu komponen mineral yang paling penting dalam menentukan nama batuan beku, serta dalam menentukan derajat pelapukan dan tingkat alterasi batuan.
Merupakan kelompok mineral yang terdiri dari plagioklas, potasium feldspar, dan feldspatoid dengan masing-masing anggotanya. Plagioklas merupakan feldspar yang mengandung Kalsium dan Natrium. Potasium feldspar merupakan feldspar yang mengandung Kalium. Sedangkan feldspatoid merupakan feldspar yang kekurangan silika. Terbentuk langsung dari kristalisasi magma, merupakan salah satu komponen mineral yang paling penting dalam menentukan nama batuan beku, serta dalam menentukan derajat pelapukan dan tingkat alterasi batuan. Salah satu mineral paling umum di Bumi. Dalam kondisi murni, kuarsa tidak berwarna, tetapi dapat beraneka warna tergantung pengotornya. Kuarsa berwarna ungu disebut ametist (kecubung), warna kuning disebut citrine, warna merah muda disebut rose, warna putih disebut milky quartz sedangkan warna hitam disebut smoky quartz. Terbentuk langsung dari kristalisasi magma atau dari sisa organisme tertentu. Stabil di berbagai lingkungan dan paling tahan terhadap pelapukan.
Salah satu mineral paling umum di Bumi. Dalam kondisi murni, kuarsa tidak berwarna, tetapi dapat beraneka warna tergantung pengotornya. Kuarsa berwarna ungu disebut ametist (kecubung), warna kuning disebut citrine, warna merah muda disebut rose, warna putih disebut milky quartz sedangkan warna hitam disebut smoky quartz. Terbentuk langsung dari kristalisasi magma atau dari sisa organisme tertentu. Stabil di berbagai lingkungan dan paling tahan terhadap pelapukan. Terbentuk pada suhu yang tinggi dan memiliki beragam warna, tergantung pada jumlah fluorin yang ada ketika mineral ini terbentuk. Dapat ditemukan pada pegmatit, granit, riolit dan beberapa urat hidrotermal temperatur tinggi. Banyak digunakan sebagai permata.
Terbentuk pada suhu yang tinggi dan memiliki beragam warna, tergantung pada jumlah fluorin yang ada ketika mineral ini terbentuk. Dapat ditemukan pada pegmatit, granit, riolit dan beberapa urat hidrotermal temperatur tinggi. Banyak digunakan sebagai permata. Umumnya berwarna abu-abu atau coklat, yang berwarna merah dinamakan rubi sedangkan yang berwarna biru disebut safir. Dapat dibuat menjadi alat ampelas yang bagus atau batu permata yang sangat mahal, terbentuk pada batuan metamorf derajat tinggi, kaya aluminium, dan sedikit silika.
Umumnya berwarna abu-abu atau coklat, yang berwarna merah dinamakan rubi sedangkan yang berwarna biru disebut safir. Dapat dibuat menjadi alat ampelas yang bagus atau batu permata yang sangat mahal, terbentuk pada batuan metamorf derajat tinggi, kaya aluminium, dan sedikit silika. Hanya terdiri dari karbon (carbon) seperti grafit tetapi memiliki ikatan yang sangat kuat, warnanya bisa bermacam-macam, mulai dari tak berwarna hingga berwarna hitam. Dapat ditemukan pada batuan ultramafik khususnya kimberlit, atau pada material endapan sungai.
Hanya terdiri dari karbon (carbon) seperti grafit tetapi memiliki ikatan yang sangat kuat, warnanya bisa bermacam-macam, mulai dari tak berwarna hingga berwarna hitam. Dapat ditemukan pada batuan ultramafik khususnya kimberlit, atau pada material endapan sungai.